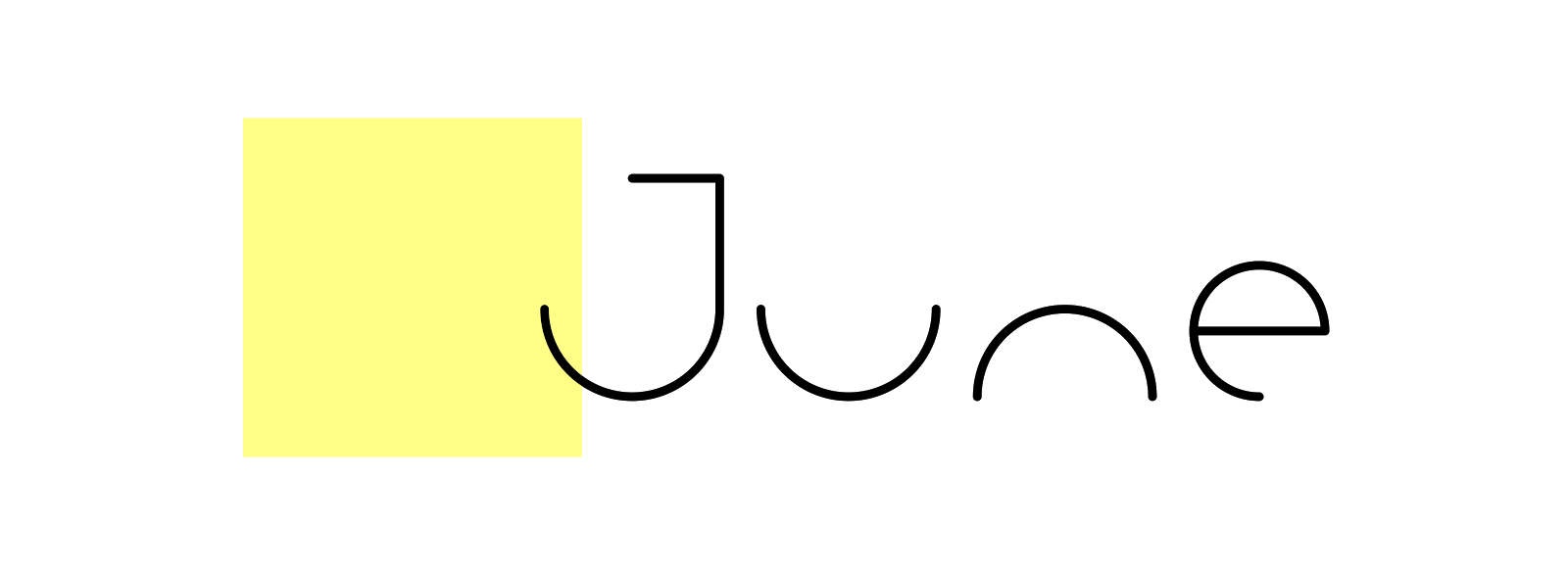Si Parasit Lajang adalah buku kelima Ayu Utami yang saya selesaikan. Ini sedikit mengejutkan. Mengingat saya punya kepercayaan terhadap diri saya sendiri kalau saya tak mungkin menghabiskan dua-tiga buku dari penulis yang sama. Ini saya membaca lima bukunya! Hebatnya lagi, buku Ayu Utami yang saya punya ada delapan. Sungguh prestasi yang perlu dibanggakan. Ah, nyatanya saya sudah membaca buku Pram sebanyak 2,5 buah dan sepertinya akan selalu jatuh cinta dengan gaya menulis Pram.
Setelah membaca buku ini (Si Parasit Lajang), yang terpikir oleh saya adalah menulis adalah salah satu cara untuk mengungkapkan pemikiran tanpa perlu diinterupsi. Meskipun nantinya akan ada kritik-kritik, setidaknya kritik tersebut tentunya adalah hasil dari pemikiran yang dikaji secara dalam dan tidak spontan.
Membaca Ayu Utami tentunya tidak akan jauh dari paham feminisme. Dan ternyata, secara tidak sadar saya memiliki pemikiran feminis sebelum saya mengerti dan paham arti feminis itu sendiri. Tapi kadang saya juga masih ragu untuk mengecap diri sendiri sebagai seorang feminis meski saya membenci patriarki dan berusaha untuk tidak seksis. Tapi toh nyatanya feminisme lebih dari sekadar itu dan saya merasa ilmu saya masih terlalu cekak untuk memproklamirkan diri sebagai seorang feminis. Oh, tentunya saya mendukung gerakan-gerakan yang bersifat feminis.
Oke, kembali ke buku.
Seperti yang dijelaskan pada sinopsis yang ada di belakang, buku ini berisi tentang cercahan pikiran seorang perempuan urban yang di akhir usia dua puluhannya ia memutuskan untuk tidak menikah dan menyebut diri si parasit lajang (sebutan yang dilontarkan oleh feminis Jepang).
Jujur, awalnya saya tak membaca sinopsis di bagian belakang buku, lantas saya mengira buku ini berisi tentang pemikiran-pemikiran feminis Ayu Utami tentang hal-hal yang menjadi alasannya untuk tidak menikah. Pada beberapa bab, Ayu Utami memang melontarkan alasan-alasannya untuk tidak menikah. Tapi ternyata buku ini tak melulu tentang itu. Buku ini tidak melulu tentang pandangannya tentang pernikahan, seks, dan segala tetek bengek yang berkaitan tentang hubungan lelaki dan perempuan. Ah, bahkan dia bercerita tentang homoseksual (yang berarti ini bukan hubungan antara lelaki dan perempuan, melainkan sesama jenis).
Sayangnya, saya tidak menulis atau memberi tanda pada bab-bab yang membuat saya setuju atau tidak setuju atas pemikirannya. Salah satu pemikiran yang saya setujui adalah pemikirannya tentang pengetahuan seks bagi perempuan. Kebanyakan remaja putri tidak saling terbuka atas pengalamannya terhadap seks. Tidak seperti remaja putra yang dengan mudahnya bercerita pengalaman seks mereka. Ini membuat kami (remaja putri) suka mencoba dan menerka untuk ‘mengenali’ tubuh kami sendiri. Hal ini sangat disayangkan sebab salah satu pengetahuan yang tidak diajarkan oleh orang tua adalah pengetahuan tentang seks.
Jika saja anak-anak perempuan lebih terbuka mengenai eksplorasi seksual mereka sejak dini, mungkin tak teralu banyak ketakutan yang mereka alami.
Seperti yang saya sebutkan di atas, buku ini tidak hanya bercerita tentang feminisme, pernikahan, dan seks. Ayu Utami juga bercerita tentang Utan Kayu (yang sekarang menjadi Komunitas Salihara), hal-hal magis yang membuatnya tertarik (sehingga ia menulis seri Bilangan Fu), asisten rumah tangganya, dan hal-hal lain yang mebuat saya tertawa satir. Beberapa pemikirannya juga kadang tak sepaham dengan saya. Sayangnya, saya tak mencatat itu semua.
Perihal seks, saya selalu suka dengan cara penyampaian Ayu Utami. Kapan-kapan saya akan bahas hal ini. Saya masih belum menemukan padanan kata untuk mendeskripsikan cara penyampaian Ayu Utami tentang seks. Ini menjadi PR bagi saya sebab sudah lima buku dia yang telah saya baca.
Pada akhirnya, saya tidak bisa memeberikan rating untuk buku ini. Karena saya sudah begitu hapal dengan gaya penulisan Ayu Utami dan tidak mungkin saya beri bintang 5/5 karena buku ini bukanlah novel yang biasa saya baca. Buku ini juga tak sesempurna itu. Saya juga merasa tidak bisa memberikan angka terhadap suatu pemikiran seseorang. Sebab benar bukanlah hal yang mutlak.
Saya juga banyak belajar dari buku ini. Dulu saya suka menulis suku kata yang baru saya temui. Buku ini menyajikan banyak suku kata (lebih ke arah suku kata yang menyajikan sebuah paham sperti -isme -is) yang belum saya tahu. Tapi sayangnya, saya tak menuliskannya. Ini menjadi evaluasi untuk saya agar tak lagi malas menyelipkan kertas di dalam buku dan membawa pena ketika membaca. Sebab tak mungkin saya berdekatan dengan ponsel pintar saya ketika membaca.
*rah