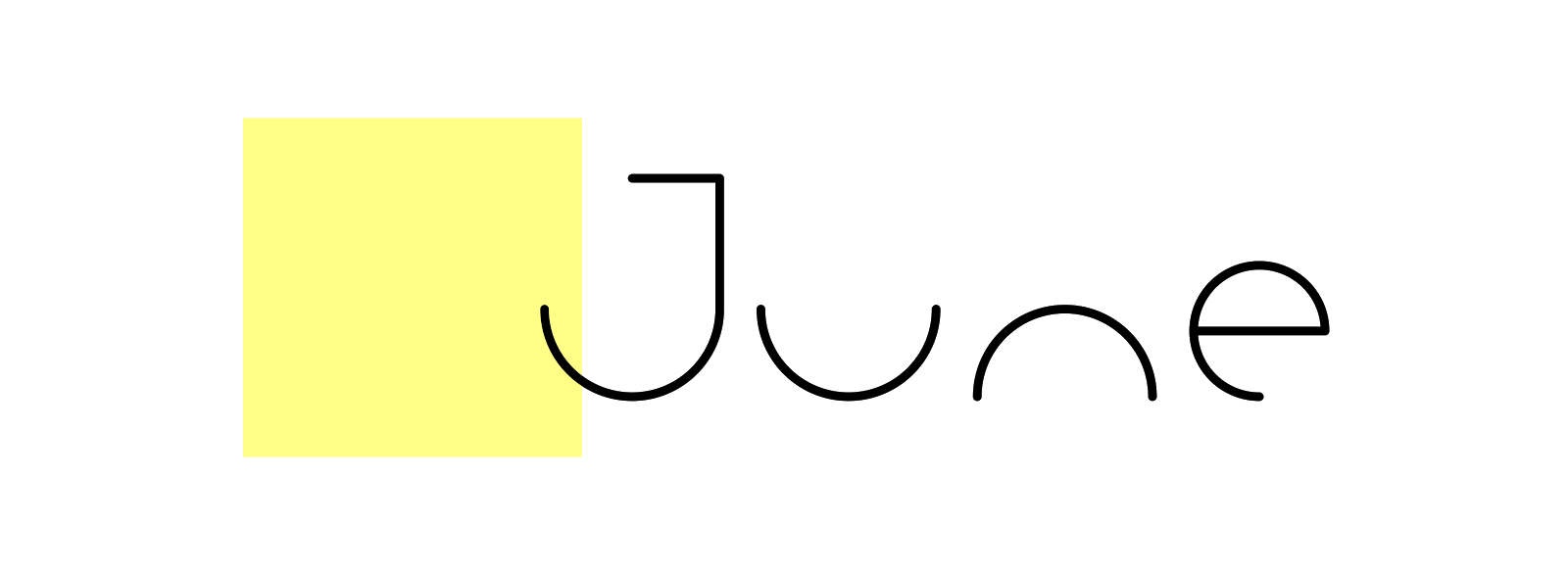Beberapa hari yang lalu(Kamis 18/01), seperti biasa ada yang mendadak ngajakin nonton film di tengah-tengah suntuk ngerjain TA. Siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Karena belakangan banyak yang sering update tentang The Greatest Showman, akhirnya saya memutuskan untuk menonton film tersebut. Bukan, bukan karena saya penasaran dan betulan ada niat nonton. Semua terjadi berdasarkan intuisi.
*
Film ini bercerita tentang perjalanan hidup P.T. Barnum dan sanggar sirkusnya. Masa kecilnya, Barnum adalah anak dari seorang penjahit yang jatuh cinta dengan seorang anak dari klien bapaknya yang bernama Charity. Charity dan Barnum saling jatuh cinta. Setelah pertemuan pertamanya, pada hari yang sama keduanya berpetualang di sebuah rumah tua. Barnum dengan mudah membuat Charity terkesima dengan caranya bercerita.
Sampai suatu ketika Charity harus menempuh pendidikan di luar kota membuat keduanya harus berpisah di dua kota yang berbeda. Tapi alhamdulillah, keduanya masih menjalin silturahim lewat surat.
Tak lama, ayah Barnum meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Barnum tetap harus bertahan hidup. Meski ia harus sering mencuri roti untuk bisa membeli kertas surat yang nantinya dikirimkan kepada Charity.
Setelah dewasa, Barnum melamar Charity.
Oke, cukup sekian saya membahas sinopsisnya. Kalau dilanjutkan, dapat menimbulkan spoiler.Tapi sayangnya, bakal ada banyak spoiler setelah ini. Hehe.
Secara keseluruhan, saya kurang suka dengan film ini. Bukan karena ini film musikal. Saya termasuk orang yang bisa menikmati dan suka dengan film musikal. La La Land, Les Misérables, dan lain-lain. Mari kita bahas satu-satu.
s t o r y l i n e d a n p l o t
Gak masuk akal. Plotnya gampang ditebak. Sekalinya salah tebak, eh gak masuk akal.
Ketika Ayah Charity menolak Barnum, saya menebak bakalan ada drama keluarga. Tetapi dengan mudahnya Charity meninggalkan ayahnya dan menikahi Barnum.
Nah, ketika Jenny Lind bertemu dengan Barnum, saya menebak bakal ada skandal. Eh, iya dong. Padahal setelah research di wikipedia, Jenny Lind dan Barnum gak ada skandal.
Endingnya? Wah kalau dibahas dari segi dramaturgi sih lebih baik tak perlu membahasnya.
m u s i k
I was expecting a time machine. Tapi apa? Musiknya too pop. Belum lagi perkara Jenny Lind. Jenny Lind diperkenalkan sebagai penyanyi opera. Tapi ketika bernyanyi, saya mbatin, "Operanya di mana nih kalo boleh tahu?"
Musiknya bagus, tapi kalau disandingkan dengan set waktunya, gak nyambung. I was expecting too much.
k o s t u m
s t o r y l i n e d a n p l o t
Gak masuk akal. Plotnya gampang ditebak. Sekalinya salah tebak, eh gak masuk akal.
Ketika Ayah Charity menolak Barnum, saya menebak bakalan ada drama keluarga. Tetapi dengan mudahnya Charity meninggalkan ayahnya dan menikahi Barnum.
Nah, ketika Jenny Lind bertemu dengan Barnum, saya menebak bakal ada skandal. Eh, iya dong. Padahal setelah research di wikipedia, Jenny Lind dan Barnum gak ada skandal.
Endingnya? Wah kalau dibahas dari segi dramaturgi sih lebih baik tak perlu membahasnya.
m u s i k
I was expecting a time machine. Tapi apa? Musiknya too pop. Belum lagi perkara Jenny Lind. Jenny Lind diperkenalkan sebagai penyanyi opera. Tapi ketika bernyanyi, saya mbatin, "Operanya di mana nih kalo boleh tahu?"
Musiknya bagus, tapi kalau disandingkan dengan set waktunya, gak nyambung. I was expecting too much.
k o s t u m
Terlalu kontemporer. Di mata saya sih agak mencolok. Seperti musik, saya berekspektasi sebuah mesin waktu. Dengan set waktu akhir abad 18an, harusnya saya bisa melihat sesuatu yang lain dari film ini. Tapi ternyata saya gak melihat apa-apa. Kecuali baju Charity yang selalu biru. Gak selalu sih, tapi kebanyakan berwarna biru.
Awalnya memang saya tidak berekspektasi apa-apa tentang film ini. Ekspektasi mulai saya buat ketika film dimulai. Tapi bukan ekspektasi berupa "Wah film bagus nih" "Wah soundtracknya menjanjikan nih" "Film musikal, bisa dilihat-lihat koreonya nih". Bukan. Saya lebih berekspektasi tentang mesin waktu yang bisa saya rasakan ketika saya melihat film ini.
Seperti dibilang di awal, secara keseluruhan saya kecewa dengan film ini. Apakah hanya karena tidak memenuhi ekspektasi saya? Iya, tapi bukan ekspektasi yang demikian. Mungkin karena saya agak sedikit gak terima dengan cara penyampaian sang sutradara yang semi kontemporer.
Memang tidak dijelaskan kalau ini adalah film biopik yang menceritakan kehidupan P.T. Barnum. Tapi beberapa karakternya ada yang beneran nyata, meski beberapa karakternya ada yang buatan atau diganti (Bailey diganti Phillip Carlyle, meski di Wikipedia dijelaskan sebagai composite character). Kejadiannya pun ada yang dibuat-buat (seperti skandal Barnum dan Jenny Lind) meski ada pula yang benar adanya (Pak Barnum bikin pertunjukan sirkus).
Atau saya yang kelewatan pernyataan 'Half Fiction Half Biopic Movie'? Atau memang tujuannya 'Half Classic Half Contemporary Movie' ya? Sorry to say, gak masuk di logika saya. Kesannya setengah-setengah. Mungkin kalau misal semua tokohnya dibuat fiktif dan ceritanya terinspirasi dari Pak Barnum, saya masih bisa menerimanya.
*
Awalnya memang saya tidak berekspektasi apa-apa tentang film ini. Ekspektasi mulai saya buat ketika film dimulai. Tapi bukan ekspektasi berupa "Wah film bagus nih" "Wah soundtracknya menjanjikan nih" "Film musikal, bisa dilihat-lihat koreonya nih". Bukan. Saya lebih berekspektasi tentang mesin waktu yang bisa saya rasakan ketika saya melihat film ini.
Seperti dibilang di awal, secara keseluruhan saya kecewa dengan film ini. Apakah hanya karena tidak memenuhi ekspektasi saya? Iya, tapi bukan ekspektasi yang demikian. Mungkin karena saya agak sedikit gak terima dengan cara penyampaian sang sutradara yang semi kontemporer.
Memang tidak dijelaskan kalau ini adalah film biopik yang menceritakan kehidupan P.T. Barnum. Tapi beberapa karakternya ada yang beneran nyata, meski beberapa karakternya ada yang buatan atau diganti (Bailey diganti Phillip Carlyle, meski di Wikipedia dijelaskan sebagai composite character). Kejadiannya pun ada yang dibuat-buat (seperti skandal Barnum dan Jenny Lind) meski ada pula yang benar adanya (Pak Barnum bikin pertunjukan sirkus).
Atau saya yang kelewatan pernyataan 'Half Fiction Half Biopic Movie'? Atau memang tujuannya 'Half Classic Half Contemporary Movie' ya? Sorry to say, gak masuk di logika saya. Kesannya setengah-setengah. Mungkin kalau misal semua tokohnya dibuat fiktif dan ceritanya terinspirasi dari Pak Barnum, saya masih bisa menerimanya.
Tapi masih bisa dibilang film ini bagus, meski saya agak sedikit kecewa. Hm, lebih banyak kecewanya sih. Hehe.
Meski begitu, film ini bikin saya research tentang P.T. Barnum, Victoria Era di Amerika, Americans Slavery, sejarah kata 'circus' jika dibedah dari sudut pandang linguistik, Musik Opera, dan beberapa hal lain yang kayaknya ditunda saja karena masih ngurusi Tugas Akhir.
Awalnya sih mau kasih rating 6/10, karena film ini cukup tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan untuk menjadi mesin waktu. Tapi jadi 4/10 karena tokoh utamanya, P.T. Barnum, bukanlah tokoh fiktif. Kalau film Indonesia sih bisa maklum ya.
Awalnya sih mau kasih rating 6/10, karena film ini cukup tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan untuk menjadi mesin waktu. Tapi jadi 4/10 karena tokoh utamanya, P.T. Barnum, bukanlah tokoh fiktif. Kalau film Indonesia sih bisa maklum ya.
*rah