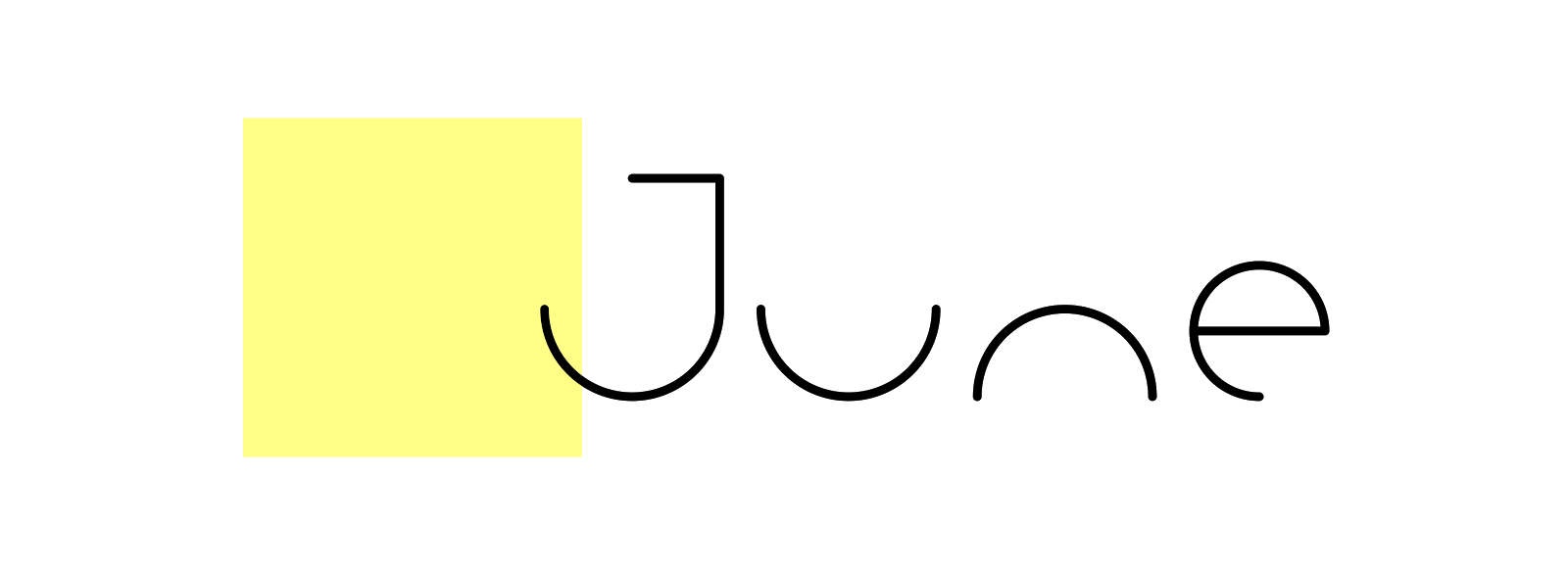+
|
Semalam percakapan kita
sampai mana ya, Mas?
|
-
|
Sepertinya Ngawi.
|
+
|
Yah, kalau Sidoarjo saja
bagaimana? Agar seolah-olah kita baru saja bercakap.
|
-
|
Kita baru saja bertemu untuk
yang kedua kalinya di kursi sebuah kereta setelah pertemuan di ruang tunggu.
Kita baru bertukar nama, lalu kau tertidur.
|
+
|
Artinya, percakapan kita
belum sampai Sidoarjo?
|
-
|
Lalu kau bangun di Ngawi.
|
+
|
Dengan bahagia!
|
-
| |
+
|
Tak jadi pulang?
|
-
|
Tak perlu. Kita mengobrol tak
ada habisnya.
|
+
|
Mau tak mau kita harus turun
di Jogja, kan?
|
-
|
Kita ke Jogja berdua tanpa
janjian dan tujuan.
|
Saturday, August 26, 2017
Sampai Mana?
Friday, August 25, 2017
Sepuluh Menit Paling Bajingan
“LDR itu bajingan. Jarak itu bajingan. Waktu yang memisahkan pun, juga bajingan.” Ujarku kepada Fajar malam tadi. Ia meneleponku tiba-tiba. Aku yang mendadak rindu, dan ia menyempatkan waktu sepulang bekerja untuk mendengarkan segala cerita dariku. Sampai hampir berganti hari, kami bertukar cerita.
Kami berteman dari SMP, dari tahun 2004. Tadi kami sempat membahasnya. Setelah lulus SMP, kami berteman baik. Lulus SMA pun, kami masih berteman dengan jarak. Kadang tiba-tiba ia meneleponku selama 30 menit dari Pontianak hanya karena ingin meneleponku. Kalimat di atas kusampaikan karena ia sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasihnya. Ia di Bali, kekasihnya di Surabaya.
Kalimat itu kulontarkan setelah kami habis membahas perbedaan waktu yang terjadi di Surabaya dan Bali yang begitu konyol dan aneh. Dan aku, terlalu konyol untuk protes mengapa jarak Surabaya-Bali nampak begitu aneh dirasakan. Aku seolah-olah pernah merasakan betapa jauh dan konyolnya waktu yang memisahkan Surabaya-Bali.
Seperti yang kita tahu, Indonesia dibagi menjadi tiga bagian waktu. WIB, WITA, WIT. Surabaya ada di bagian WIB, sedangkan Bali –atau selanjutnya kita sebut Denpasar saja– berada di bagian WITA. Jaraknya cukup satu jam. Tak seperti Surabaya-Sorong. Tapi ada yang aku benci dengan pembagian waktu ini.
Jika dilihat dari pergerakan matahari, Surabaya-Denpasar hanya berjarak 10 menit. Contohnya saja ketika sahur. Denpasar lebih dulu imsyak (ini jelas). Tak perlu memakai patokan waktu WIB-WITA, sepuluh menit kemudian Surabaya imsyak. Tapi jika dilihat dengan memakai waktu WIB-WITA, imsyak Denpasar terjadi pada pukul 5.00 WITA. Sedangkan imsyak Surabaya terjadi pada pukul 4.10 WIB. Ini menyebalkan. Yang harusnya terasa sepuluh menit, malah terlihat berjarak satu jam.
Aku marah-marah protes di telepon seolah-olah pernah merasakannya. Aku pernah merasakannya. Dengan Adyatarna. Ah, anggap saja sudah. Itulah mengapa aku berkata kepadanya bahwa jarak itu bajingan. Bukan karena memisahkan, terlebih karena membuat waktu menjadi konyol dan tidak masuk akal.
Jika nanti memang jarak yang membuat aku –dengan entah siapa nanti– menjadi dekat, semoga logika dapat mematahkannya menjadi hal yang tak konyol dan lumrah.
Jarak dan waktu telah mengelabui kita, Adyatarna. Ah, ataukah pemerintah? Ketika itu ingin rasanya mengubah aturan pembagian waktu WIB dan WITA menjadi waktu kesepakatan kita berdua saja. Tapi tak bisa. Nanti kita terlalu bersepakat dengan banyak hal.
Monday, August 21, 2017
Jogjakarta dan Seorang yang Lain
Jika tulisan sebelumnya saya mengusulkan untuk mendengarkan lagu Adhitia Sofyan yang berjudul Sesuatu di Jogja, kali ini saya juga akan mengusulkan sebuah lagu untuk menemani kalian membaca tulisan yang panjang. Masih dari musisi yang sama dengan judul berbeda. Judul lagunya 8 Tahun. Bisa didengarkan secara online di Spotify dan SoundCloud.
*
Ketika patah hati dengan orang Jogja yang kemarin saya ceritakan, otak saya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan hati saya. Ia membuatkan saya seorang teman imajinasi bernama Galang Adyatarna. Galang Adyatarna hadir dengan pelan-pelan menjadi pelarian saya. Selama perasaan saya belum habis kepada orang Jogja satu itu, otak saya membuat fantasi-fantasi indah dan gila bersama Galang Adyatarna.
Sunday, August 20, 2017
Surat Cinta: Tentang Jogjakarta dan Seseorang
Sebelum membaca tulisan ini, izinkan saya untuk mengusulkan sebuah lagu yang didengarkan sebagai pengiring membaca tulisan ini. Sebab tulisan ini ditulis dengan mendengarkan lagu tersebut. Sesuatu di Jogja oleh Ahitia Sofyan. Bisa didengarkan secara online di Spotify, dan SoundCloud. Barangkali tulisan kali ini agak sedikit panjang.
*
Jogja, entah mengapa selalu memiliki kemampuan untuk mengubah. Tempatnya, pun orang-orangnya. Bagi saya, keduanya memiliki peran penting di hidup saya. Jogjakarta, dan orang Jogjakarta. Jogja pernah membantu saya membersihkan residu perasaan kepada seseorang. Dikuras habis oleh orang yang bersangkutan.
Wednesday, August 9, 2017
Friday, August 4, 2017
Balasan kepada K
Barangkali, hanya di hadapannya aku tak dapat menahan rindu. Bahkan, jika rinduku harusnya disampaikan untuk orang lain, maka akan kuutarakan kepadanya. Sepertinya, semua rindu hanya menuju untuk ia.
“Aku rindu merayakan ulang tahun berdua.”
“Maret masih lama,” katanya di seberang.
“Tak bisa kah kita rayakan tiap setengah tahun sekali?”
“Bisa tiap hari. Dirayakan bersama orang yang selalu bersyukur akan kehadiran kita di tiap harinya.”
Maret lalu, ia manusia terakhir yang memberikanku ucapan selamat ulang tahun via telepon. Dan aku adalah manusia terakhir yang menemani menghabiskan tanggal istimewanya. Lucunya, meski tanggal ulang tahun kami tidak sama, tahun ini kami sama-sama menghabiskan hari ulang tahun kami dalam sebuah perjalanan menuju Surabaya. Aku di bus, ia di kereta lima hari kemudian. Lalu selang beberapa hari setelahnya, kami meniup lilin di atas kue yang sama. Di sebuah kota yang mempertemukan kami. Surabaya.
Berbicara tentang rindu, tadi malam kami membahasnya. Katanya, kepekatan rindu dapat diukur dari jarak waktu yang mengutarakan. Jika diutarakan tiap hari, maka rindu itu encer. Jika sebulan sekali, rindu itu pekat. Kuiyakan. Tapi ia protes. Malam tadi ia banyak protes.
“Lemah! Main setuju saja? Tak kau sanggah atau protes?”
Terserah. Yang jelas, dini hari tadi kami menghabiskan satu setengah jam mengobrol. Entah kapan terakhir kali kami mengobrol tak ada juntrungnya sampai ia menanyakan, “Kita nih membicarakan apa, sih?”
Aku masih mengingat kalimatnya tiga tahun yang lalu. Kami bertemu di sebuah restoran fast food. Kami memutuskan untuk bertemu setelah sadar kalau lima pertemuan sebelumnya tak pernah sampai lima menit. Selepas pertemuan itu, sebelum berpisah, ia berkata, “Ini kalau diteruskan, bisa sampai subuh.”
Di telinga kami, tak ada yang salah dengan ceracau dan Bahasa Kesepakatan yang-sejatinya-tak-pernah-disepakati. Orang-orang seperti kita. Itu yang selalu ia ucapkan. Padahal aku tak paham seperti apakah kita ini, K?
Tadi malam kami juga bicarakan tentang surat. Yang aku ingat tentang Palembang-Surabaya adalah jarak yang ibu dan bapakku ciptakan untuk bertukar kabar via surat. Lantas ia bercerita kalau ia rindu berkirim surat. Kenapa kita tak berkirim surat saja, K?
“Di sini tak ada kantor pos. Kan aku di hutan.”
Jika memang jodoh tak hanya untuk pasangan yang akan menikah nantinya, kita ini berjodoh, kan, K? Teman juga jodoh, kan?
Kami telah sepakat tentang hal ini.
Subscribe to:
Posts (Atom)