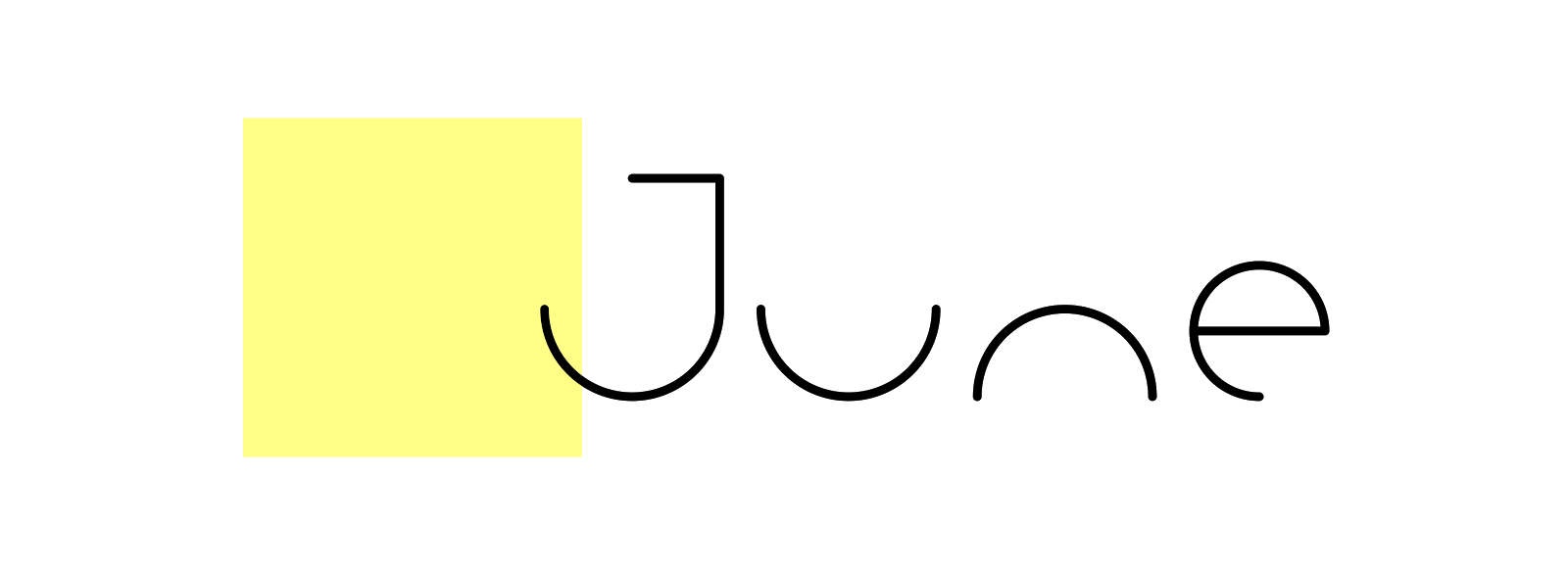Pagi-pagi betul—tepatnya selepas subuh, Adya datang ke rumah. Seperti biasa, ia mengenakan baju dinas andalannya: kaus abu-abu lusinan, jaket butut merah marun, celana khaki selutut, tas selempang kanvas berwarna coklat, dan sandal gunung butut.
"Pagii!" begitu sapanya dari atas sepeta butut milik pamannya dengan gigi meringis ketika aku mulai berjalan ke arahnya.
Tentu saja aku menyambutnya dengan wajah yang ditekuk karena ia menjemput terlalu pagi tidak sesuai janji. "Subuh! Masih subuh ini, Mas!"
Ia tertawa. Kali ini singkat, tidak terlalu lepas seperti biasanya. Sebab jika ia tertawa lepas, aku nanti yang kerepotan mengumpulkannya menjadi satu. Ia menyalakan mesin motornya. Aku langsung saja menaiki jok belakang motornya.
"Siap?" tanyanya. Tanpa perlu menunggu jawabanku, ia langsung melaju.
Tujuan pertama kami adalah Pantai Timur untuk melihat salah satu fenomena alam favoritnya: matahari terbit. Kebetulan semalam baru saja terjadi fenomena favoritnya yang kedua: purnama. Sehingga air laut agak sedikit naik dengan ombak yang masih pasang.
Sesampainya di Pantai Timur, langit masih gelap. Kami memutuskan untuk menelusuri tepi pantai untuk menunggu matahari terbit.
Kami berpapasan dengan nelayan yang baru saja menepi. Tanpa pamit, ia tiba-tiba saja berlari-lari kecil menuju nelayan-nelayan itu. Aku menghela napas, hapal dengan tabiatnya, lalu melanjutkan langkah kakiku setelah mengisyaratkan kepadanya kalau kalau aku akan ke tempat yang aku tunjuk. Ia mengangguk.
Aku berjalan, memilih tempat yang aman untuk duduk sambil memandang cakrawala timur dan menikmati debur ombak pasang yang bergemuruh. Sesekali aku melihat Adya dari kejauhan. Ia begitu luwes bergaul dengan bapak-bapak nelayan. Sampai tak berapa lama, ia menuju ke arahku dan…membawa segepok ikan.
Dia tak suka ikan, apalagi ikan laut. Untuk apa membawa ikan sebanyak itu?
Setelah mendekat, ia langsung menjelaskan sambil menyerahkannya kepadaku, “Untuk ibu masak di rumah. Kamu dan adik-adikmu kan suka banget ikan laut.”
Aku mengernyitkan dahi. Aku tak akan pernah mengerti bagaimana caranya berpikir. Tapi aku terima saja ikan pemberiannya sambil berucap terima kasih.
Ia duduk di sampingku, memandang langit yang sama. Kali ini benar-benar sama.
“Dya, apakah buku laksana matahari? Sebab keduanya memiliki kegiatan yang sama: terbit,” tanyaku tanpa menatapnya seperti kebiasaanku sebelumnya.
“Barangkali iya. Keduanya juga menerangi. Matahari beri cahaya, buku beri ilmu. Cahaya dan ilmu sama-sama menerangi. Terang pada ilmu tak hanya isyarat atau perumpamaan. Kamu pasti sering dengar kalimat ‘si A menerangkan hal baru kepada si B,’” terangnya panjang lebar.
“Apakah di bawah cakrawala terdapat percetakan?”
“Mungkin. Barangkali ada.” Kami diam sejenak. Lalu ia melanjutkan, “Ini kita sedang nunggu prapesan matahari, sebab matahari belum terbit, tapi kita sudah di sini.”
Kami tertawa.
Ia berujar lagi sambil menunjukkan tangannya, “Kalau matahari tinggi sedikit, bilang saja best seller. Kalau matahari sedang tepat di atas kepala kita, namanya mega best seller.“
“Di Surabaya mataharinya selalu mega best seller,” aku tiba-tiba menyahut. Kami tertawa lagi.
“Tapi ketika ia hendak tenggelam, ia menjelma manusia: renta.”
Aku menatapnya, melengkapi kalimatnya, “Lelah di mana-mana, raung klakson merengek minta pulang, apalagi?”
Ia menggeleng. “Itu kan kota. Ini matahari dan manusia.”
Aku memandangi cakrawala yang menyebarkan cahaya oranye.
“Tak punya daya dan seakan hendak menyerah sebab cahayanya makin redup?” tanyaku dengan memandangnya lagi. Ia mengangguk.
Ia membalas tatapan mataku. “Lalu pulang. Banyak yang pulang ketika matahari hendak tenggelam atau ketika manusia telah menua.”
Pulang adalah kata yang paling sering kami ucapkan. Bagi kami, pulang tak melulu tentang rumah. Aku memandangi matanya dalam-dalam. Aku mencari-cari, menunggu argumen apa yang terlontar darinya tentang pulang kali ini.
Ia meringis, mengusap puncak ubun-ubun kepalaku. “Ngapa da dipikir? Tengok ja lah itu langitnya.”
Kami kembali memandangi langit dengan latar suara ombak. Sesekali aku memejamkan mataku, mendengarkan suara alam paling indah.
Matahari perlahan naik merangkak. Aku memandang manusia di sebelah kananku sekali lagi. Kini ia yang memejamkan matanya. Garis-garis wajahnya begitu semakin tegas ketika diterpa cahaya lembut dari matahari pagi. Ia tersenyum, aku mengikutinya.
“Aku tak pernah melihat matahari terbit seindah ini,” kataku.
“Lha yen tangimu awan terus, piye nek mu mbandingke?” tanyanya. Ya kalau bangunnya siang, gimana caramu membandingkan?
“Aku tuh bisa tauk jadi morning person. Cuma males aja nyari spot buat lihat matahari terbit,” sanggahku.
“Tur ra enek sing keno dijak ndeleng ngenean isuk-isuk?” ia menegaskan. Belum lagi tidak ada yang bisa diajak lihat beginian pagi-pagi?
“Lha mesti apes og. Yen ndeleng dewe i iso uapik. Mesti apik. Yen ngajak kanca, mesti zonk. Mendung. Ndeleng dewe mager, ngajak konco zonk. Kan hadeh,” protesku. Selalu apes. Kalau lihat sendiri bisa baguuus banget. Selalu bagus. Kalau ngajak temen, selalu zonk. Mendung. Lihat sendiri mager, ngajak temen zonk. Kan hadeh.
“Bedjo, we, dino iki,” tiba-tiba ia menarik kesimpulan. Kamu beruntung hari ini.
“Iya. Panitia penerbitan mataharinya canggih, nih. Dah lihatnya ada temen, bagus pun. Dapat souvenir ikan segepok pula.”
“Ini belum apa-apa, Nyit.”
“Ah iya. Baru pagi, ya.”
“Huum. Baru pembukaan. Penilaian panitia diadakan nanti malam.” Ia berdiri, mengulurkan tangannya, mengajakku berdiri. “Yuk, masih ada beberapa tempat lagi yang harus kita kunjungi.”
Aku menyambut uluran tangannya dan ikut berdiri. Kami lalu berjalan menuju parkiran. Kami menaiki motor dan melaju ke destinasi selanjutnya: sarapan.
Menurut kami, pagi yang sempurna adalah pagi dengan sarapan bubur ayam. Kami tiba di salah satu tempat bubur ayam langganan.
“Mang, kayak biasanya, ya. Dua. Satu jumbo, satunya biasa. Yang jumbo pake telor, yang satu ga pake telor. Minumnya…air putih aja,” pesanku ke mamang penjual bubur ayam.
“Merica dan kecap asinnya ambil di situ, ya,” katanya sambil menunjuk botol merica dan kecap asin yang berbaris di tempat yang tidak bisa ia jangkau.
Aku tersenyum dan mengambil botol merica dan kecap asin tersebut, dan berjalan menuju kursi yang telah disiapkan Adya tak jauh dari tempatku berdiri. Ada tiga kursi. Satu kursi telah ia duduki, satu kursi sebelah kirinya untuk aku duduki, dan satu kursi di depan kami. Aku meletakkan merica dan kecap asin di atas kursi kosong tersebut.
“Nyit, nanti pulang dulu aja, ya. Karena nanti kita bakal main sampai malam, sepertinya kita butuh mandi dan memakai baju yang layak.”
“Oke.”
“Pakai baju yang belel, ya.”
“Kok ngatur? Katanya layak, kok belel?”
“Karena destinasi-destinasi kita nanti akan lebih menyenangkan kalau pakai baju belel. Dijamin, kalau kamu pake dress lalu aku pakai kemeja safari, ga bakal cocok. Layaknya ya pake baju belel.”
Aku memandangnya dengan menyipitkan mata curiga.
“Udah, percaya aja ka aku.”
Dua mangkuk bubur pesanan kami datang. Kami berdua menerima mangkuk tersebut sambil tersenyum dan berterima kasih.
“Kita mau ke mana, sih?”
Adya diam saja. Ia fokus mengaduk buburnya.
“Dya, kita kamu ke mana? Nyasar dulu? Nyasar bukan destinasi, ya.”
Ia menarik napas, meletakkan sebentar buburnya yang masih setengah teraduk. “Kali ini kita punya destinasi. Nanti aku kasih tahu. Sekarang kita makan dulu, ya.”
Aku menurut. Lagi. Kami fokus menikmati makanan kami hingga habis.
Setelah mengembalikan mangkuk dan membereskan sampah yang kami buat, kami membayar sarapan bubur kami. Kami beranjak. Adya mengantarkanku pulang.
Baru saja aku turun dari motornya, Adya langsung menodong perintah, “Gak perlu lama-lama, ya, siap-siapnya. Sejam cukup, kan? Sekarang pukul tujuh, satu jam lagi aku sampai sini.”
“Cepet banget,” protesku.
“Sayang aja sih kalau waktunya dibuang. Aku juga akan siap-siap sekilat mungkin, kok. Lima belas menit dari sekarang aku baru sampai kontrakan. Mandi dan siap-siap setengah jam cukup. Lalu jalan lagi ke sini lima belas menit. Ya paling molor lima sampai sepuluh menit lah. Cukup?”
Aku ingin protes lagi. Sebetulnya satu jam adalah waktu yang cukup untukku siap-siap. Tapi aku rindu kasurku. Aku ingin goleran agak lama sedikit.
Adya memberikan penawaran lagi, ”Nanti pas aku jemput, aku kasih tahu kita akan ke mana. Kita taruhan. Kalau tujuannya tidak membuatmu senang, kita bisa batalkan acara kita hari ini.”
Melihat wajahnya yang tegas dan serius, aku tak berani merengek dan meminta macam-macam lagi. Lagi-lagi aku menurutinya.
Adya menyerahkan ikan segepok yang ada di kemudinya sambil mengingatkan, “Jangan lupa pakai baju belel dan sepatu, ya. Kaos oblong dan jaket sudah cukup.”
Aku menerima ikan itu dan mengiyakan peringatannya yang sekaligus memberikanku ide harus pakai baju apa sehingga aku tak perlu berpikir lebih banyak untuk memutuskan memakai baju apa. Kaos dan jaket sudah cukup, jangan lupa sepatu. Oke.
Aku berpesan hati-hati. Ia mengangguk dan melaju pergi. Aku melihat punggungnya menjauh. Ketika punggungnya tidak terlihat lagi, aku masuk rumah.
Sampai di dalam rumah, aku meletakkan ikan ke dapur dan mencuci tanganku. Kemudian aku berlari ke kamar dan membuka lemari, melihat baju bersih yang tersedia dan cocok dengan syarat jalan-jalan kali ini. Kaos oblong dan jaket…ada!
Aku segera mandi dan bersiap diri. Ternyata, tak butuh waktu satu jam. Sisa waktu yang tersisa aku gunakan untuk menunggu di ruang tamu sambil selonjoran.
Tak berselang lama, tepat pukul delapan, suara motor butut Adya terdengar dari ruang tamu. Aku ke dapur mengecek tak ada kompor yang menyala, ke kamar mandi mengecek kran tidak menyala, dan ke kamarku sendiri untuk mengecek tidak ada perangkat listrik yang menyala, lalu aku keluar rumah.
Dari dalam pagar, Adya terlihat mengenakan kaos oblong, flannel kota-kotak merah putih, celana jeans belel, dan sepatu converse high favoritnya. Nampak normal seperti biasanya. Namun ketika mendekat ke sampingnya, aku kaget dengan detil dari baju yang ia kenakan.
Sepatu favoritnya yang ia kenakan itu kini telah menua. Aku ingat betul sepatu itu dulu berwarna biru navy. Kini berubah menjadi hampir abu-abu. Belum lagi solnya yang sudah sah menipis dan lem yang lepas di bagian samping sepatu.
Naik sedikit ke celananya. Aku yakin, celana jeans yang ia gunakan tidak dicuci selama dua bulan. Ada robekan sedikit di lututnya yang sebentar lagi pasti akan melebar.
Lalu naik lagi ke atasannya. Aku tidak kaget dengan flannel kotak-kotak merah putih yang sedikit memudar. Ia sering mengenakan kemeja tersebut. Namun kaos oblong yang ia kenakan membuat mataku melotot. Dari dekat, kaos oblong berwarna krem itu terdapat robekan tipis nyaris bolongdi bagian jahitan leher. Aku familiar dengan kaos ini.
“Aku kayaknya ada pernah kenal dengan kaos ini,” aku memastikan.
Dengan bangganya ia menyibak flannelnya dan memperlihatkan gambar yang disablon di dada sebelah kiri: FSRD09. Kaos ospek ketika ia maba masih ada. Kaos yang sama itu terakhir kali aku lihat delapan setengah tahun yang lalu ketika mampir di kontrakannya di daerah Tukad Badung, Denpasar Timur, ketika ia sedang menjadi mahasiswa tingkat akhir dan sibuk mengurusi administrasi kampus setelah pameran dan sidang. Robekan yang ada di jahitan leher itu ada karena ia sering menggigitnya ketika berpikir atau sedang mengerjakan sesuatu.
"Tua banget??!!"
"Seusia perkenalan kita," godanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Lalu ia mengarahkan pandangannya naik turun kepadaku. Melihatku yang mengenakan celana berwarna krem, kaos biru dan jaket abu-abu. “Cosplay langit mendung?”
“Yoi. Biar hari ini terang. Sebab mendungnya sedang kukenkan.”
“Akan selalu terang, kan kamu bersamaku.” Galang adalah bahasa Bali yang artinya terang. Terang langit yang tidak mendung. Terang yang cahaya.
“Sesuai janjimu, kamu akan menjawab pertanyaan destinasi kita hari ini,” tagihku.
Ia tersenyum. “Kita nanti akan muter-muter ke tempat-tempat kesukaan kita. Malamnya, destinasi utama kita adalah…Kabelegi.”
Aku membelalakkan mata dan mulutku, nyaris memekik berteriak. Sontak, aku melompat-lompat dan menarik-narik lengannya. Kabelegi. Tempat nun jauh yang telah lama kita perbincangkan dan dambakan.
“Aduh, aduh, makin robek nanti, Nyit,” ia mengaduh sambil memegangi kemeja flannelnya.
Aku segera naik di jok belakangnya dengan sedikit melompat, tanpa peduli keseimbangan yang Adya miliki, menepuk pundaknya, dan berteriak, “Lesgo!!”
Kami melaju memecah jalanan. Aku tak sabar dengan destinasi utama kami. Aku juga tak kalah penasaran tempat-tempat yang akan kami kunjungi.