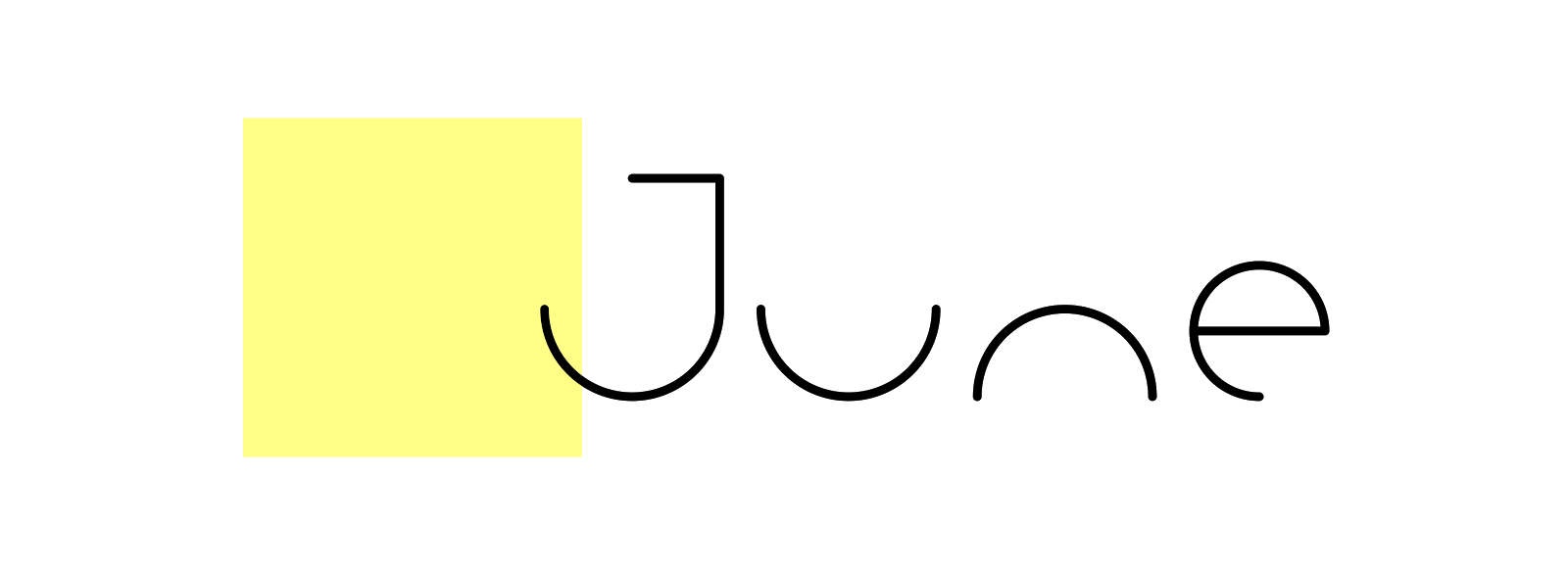Sebetulnya sudah lama saya kepingin bahas hal seperti ini di
blog. Sebab ada rasa yang menggelitik di otak yang rasanya sudah lama dipendam
dan ingin ditumpahkan.
Nah, kebetulan, tadi ketika iseng buka twitter, linimasa
mendadak keluar tweets dari Bli @eshasw 2 hari yang lalu yang membahas tentang
budaya di Indonesia.
Saya jadi tergelitik untuk membahasnya.
Tidak bermaksud membantah, sih. Karena memang itu benar adanya. Tapi saya hanya
mencoba mengungkapkan apa yang saya lihat dan pikirkan tentang hal tersebut.
Budaya. Lebih khusus lagi tentang kesenian tradisional.
Karena ponsel pintar saya yang sudah
bulukan dan ya-begitulah-adanya telah menemui ajalnya, maka saya akan mencoba
membahasnya di sini lebih panjang.
*
Indonesia ini kaya. Banyak suku, bahasa,
adat, pulau, dan lain-lain. Nah, ini kenapa Indonesia amat susah disatukan,
sebab kita sangat ‘beragam’. Bahkan, perlu semboyan ‘Bhineka Tunggal Ika’ agar
kita dapat menyatu. Padahal, menurut saya, itu cuma sugesti (kapan hari akan
saya bahas).
Dengan keberagamannya itu, harusnya
kita (pemuda harapan bangsa) menaruh andil besar dalam pelestarian adat dan
budaya. Salah satunya dengan cara mengapresiasi dan mengenali kesenian
tradisional. Sayangnya, seringkali ‘pengumuman’ pertunjukan tersebut tidak
sampai kepada kita.
Tidak sedikit dari kawan saya yang
menodong info pertunjukan tradisional di Surabaya. Kapan dan dimana. Saya sih
tidak keberatan. Hanya saja... sifat saya yang males-ngajak-orang bikin bete
kawan-kawan ketika update di media sosial tentang pertunjukan yang barusan saya
lihat sendiri. Check in, upload foto, mini review, dan sebagainya.
Sayanya juga gregetan sama
pemerintah. Kenapa bikin pengumuman yang seperti ini ...
Bahkan, saya pun, yang memotret
sekaligus menguploadnya ke salah satu media sosial, lupa untuk datang ke
pertunjukan tersebut.
Saya akui, mereka sudah memiliki
pasarnya. Di Balai Budaya Jawa Timur, datang 30 menit sebelum pertunjukan pun,
bisa-bisa kamu sudah di tolak di depan gedung pertunjukan karena kursi sudah
penuh. Kalau mengadakan pementasan di Balai, datang tepat waktu saja, harus
siap-siap berdiri dan terhalang pilar-pilarnya. Sebal, kan? Ini juga mengapa
saya sering enggan mengajak orang. Soalnya, kalo rame-rame, gak bakal bisa
nyelip ketika penjaga gedung sedang lengah.
Apalagi kalau mengundang Kirun,
menampilkan Janger Banyuwangi, atau Reyog Ponorogo.
Mereka (seperti) sudah memiliki pasarnya.
Masyarakat sekitar dengan usia 40an ke atas. Maka itu pengumuman yang dipasang (yang
sebetulnya gak anak muda banget), bisa memikat masyarakat yang tersebut. Tapi
tak jarang juga pemuda seusia saya menyempatkan waktu untuk datang. Padahal,
pemuda lainnya yang tertarik bakalan datang kalau informasi tersebut sampai ke
telinga mereka.
Saya pernah ngobrol dengan
penggiat Wayang Orang yang sanggarnya sudah ‘sepi’. Mereka bilang, “Kami senang
jika pertunjukan kami diapresiasi. Apalagi dengan anak muda. Sebab kalian lah
yang meneruskan ini semua, Nak.”
Mereka menginginkan apresiasi dari
pemuda. Tapi, pengumuman mereka jarang sampai dan melekat di otak kami. Bahkan,
poster dan media publikasi ‘nyaris tidak pernah sampai’ ke mata kami.
Analisa saya : kurang adanya
komunikasi antara pemerintah sebagai penyelenggara, dan kami sebagai generasi
muda.
Lah, bukannya ada Duta Pariwisata atau seperti Cak dan Ning (di
Surabaya)?
Hm.. saya sebetulnya kurang tahu
juga apa fungsi mereka. Lagi pula, saya tak hendak membahas hal seperti itu.
Jadi sebenarnya, akan selalu ada
pemuda yang peduli dan paham tentang budaya lokal. Tapi, kebanyakan dari kita,
seringkali gampang ‘dirasuki’ oleh pop
culture yang impor. Kalau tidak dikuatkan kecintaannya dari kecil, ya bakal
dengan mudah ‘dirasuki’ budaya-budaya seperti itu. Seperti yang diungkapkan
Maestro Tari Indonesia, Didik Nini Towok (kurang lebih seperti itu).
Lebih parahnya lagi, ngimpor
budaya yang gak pop, menjadikannya sebagai kebiasaan hidup, dan menyisihkan
budaya lokal dengan sebelah mata. Seperti misalnya, menikah tanpa menggunakan
adat. Entah, saya kurang setuju. Sebab, bukankah kita sedang bermasyarakat di
sebuah negara yang masyarakatnya selain memiliki agama, juga memiliki kekayaan
adat dan budaya?
Saya tak bisa membayangkan Indonesia tanpa adat dan budaya yang diwariskan. Saya juga tak hendak memaksa mereka yang skeptis. Mendingan memecahkan masalah dari analisa di atas.
Maafkan teknik fotografi saya yang kurang. Memang gak bakat.
*
 |
| Wayang (n) : Bayangan Dari sisi seperti ini seharusnya wayang dilihat. |
*
Maafkan teknik fotografi saya yang kurang. Memang gak bakat.
×××,
Rahmadana Junita
ps : Tulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan TA
kok sudah subuh sih?