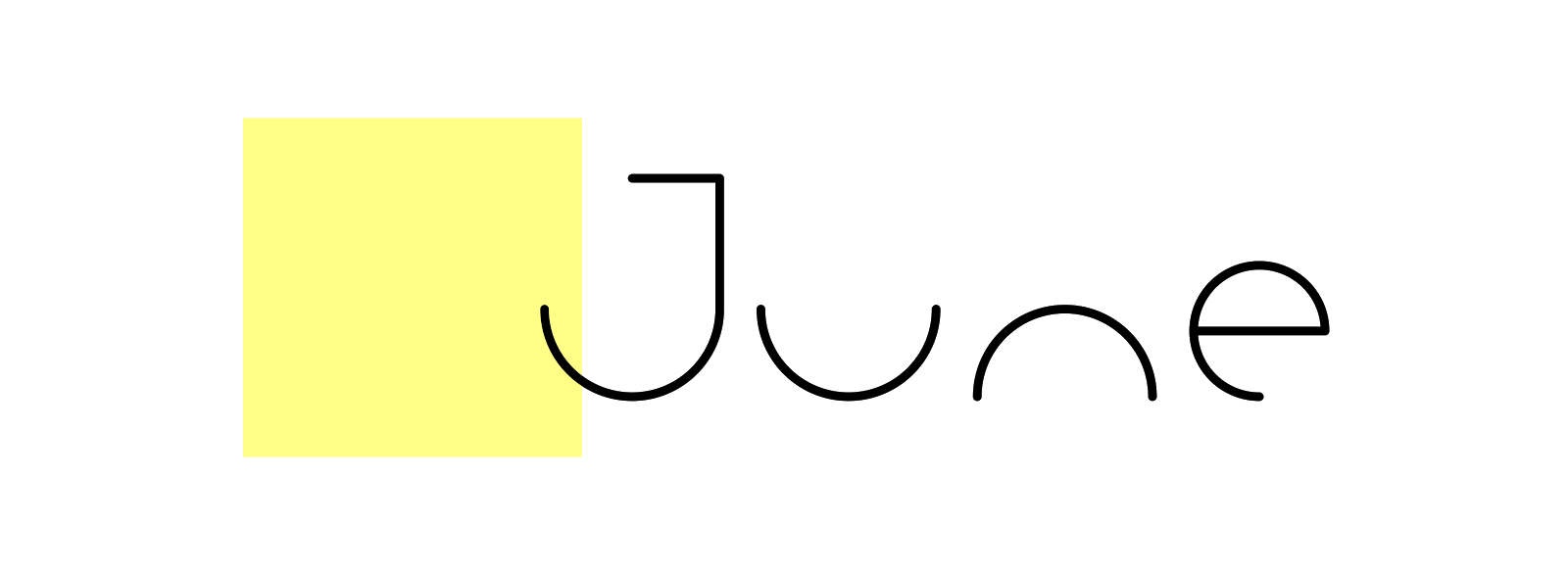Satu sampai dua tahun belakangan saya amat susah menyelesaikan satu buku. Biasanya, saya meletakkan kembali buku tersebut di rak sebelum saya sampai pada akhir buku. Siang ini tiba-tiba saja buku ‘Isinga : Roman Papua’ menyembul dari barisan buku di rak. Tersisa kurang lebih 40 halaman yang belum terbaca.

*
Sinopsis
Selang beberapa hari, Malom datang. Ia minta Irewa pulang. Mama Kame dan Bapa Labobar tak bisa mencegah. Malom adalah suami yang sah. Orangtua Malom sudah membeli Irewa dengan sejumlah babi-babi sebagai mas kawin. Selain itu, Irewa juga seorang yonime, juru damai dua pihak yang bermusuhan. Irewa harus mau untuk kembali ke Hobone. Kembali ke kehidupan sehari-harinya yang berat. Mau atau tidak, ia harus menjalaninya. Tak ada pilihan.
Kehamilan demi kehamilan, keguguran demi keguguran tidak mengurangi niat Malom untuk terus punya anak. Malom berpikir itu sudah menjadi tugasnya sebagai laki-laki. Tugas yang diminta masyarakat. Suami harus mengawini istri agar menghasilkan anak. Perempuan adalah makhluk yang mendatangkan kesuburan. Anak laki-laki berguna untuk menuntut pengakuan akan tanah dan simbol penerus keturunan. Makin banyak anak laki-laki, makin berharga dan bermartabat. Tanah luas dan keturunan banyak. Anak laki-laki juga berguna agar prajurit mati ada yang menggantikan. Anak perempuan bernilai ekonomi. Perempuan berguna untuk mendapatkan mas kawin dan harta adat (babi).
*
Ringkasan
Di Aitubu, Papua, laki-laki hanya pakai koteka, dan perempuan hanya menutup kemaluannya (entah dengan apa dan entah kemaluan yang mana). Namun ketika bertemu, keduanya tidak saling bertukar salam dan sapa. Bahkan perempuannya akan menunduk. Mereka-mereka yang takut akan leluhur akan menjaga segala interaksi lawan jenis sampai mereka sah menikah. Untuk mendekati perempuan saja butuh perantara. Kepercayaan akan leluhur dijunjung. Mereka takut akan malapetaka, kutukan, penyakit, dan segala hal buruk yang akan menimpa mereka jika melawan peraturan. Upacara-upacara adat dan ritual-ritual diselenggarakan agar mereka terhindar dari mara bahaya.
Meage mencintai Irewa. Ia ingin memperistri Irewa. Meage tahu bahwa Irewa juga merasakan hal yang sama. Ada suatu tradisi di Aitubu untuk menyampaikan rasa cinta dari seorang lelaki kepada perempuan yang dicintainya. Yaitu dengan memberikan betatas dan sayuran. Meage melakukan hal itu. Ia meminta tolong seorang teman untuk menyerahkan keduanya kepada Irewa. Si perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolaknya. Tentu saja Irewa menerima barang pemberian dari Meage tersebut. Meage siap mempersunting Irewa dengan segala bekal kebun dan babi yang telah ditabungnya.
Namun ketika upacara menstruasi pertama Irewa selesai, ia diculik.
Review
Membaca cerita fiksi dengan latar adat dan budaya dari suatu suku di Indonesia selalu menjadi hal yang menarik buat saya. Saya bisa menikmati cerita, menjelajahi ragam budaya, sekaligus ‘mampir’ di tempat yang menjadi latar cerita berlangsung. Tiap kejadian dan fakta yang disajikan selalu membuat saya berdecak. Salah satunya dengan gaya berpakaian di Aitubu seperti yang saya tulis di atas. Dari sini saya bisa lihat bahwa pelecehan seksual terjadi bukan karena busana yang dikenakan si perempuan. Penduduk Aitubu juga masih memiliki kepercayaan terhadap leluhur dan dinamisme. Kepercayaan inilah yang membuat mereka takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma.
Banyak pesan yang disampaikan dari buku ini. Tidak ada post it atau catatan-catatan kecil yang saya buat. Karena memang menurut saya pesan yang disampaikan semuanya berlanjut di satu buku. Apalagi ketika penulis menceritakan tentang keteguhan hati, mental, dan fisik Irewa dalam mengasuh keempat anaknya. Penulis begitu apik menjabarkan keteguhan Irewa lewat narasi panjangnya yang tidak membosankan. Apalagi ditambah dengan percakapan yang minim. Menurut saya, penulis cukup kuat dalam menuliskan narasi.
Ada banyak jurnal dan artikel yang membahas tentang diskriminasi gender yang terkandung dalam novel ini. Saya merasakan hal tersebut. Ada sedikit perasaan tidak terima dan marah. Tapi tokoh-tokoh perempuan yang ada dalam novel ini sedikit mampu menyembuhkan perasaan itu. Mereka saling berhubungan, terkoneksi, dan membantu satu sama lain. Tak ada tokoh perempuan yang saling menyakiti atau memusuhi. Seharusnya ini bisa diterapkan di kehidupan nyata.
Ada dua hal yang membuat saya penasaran ingin terus membaca buku ini. Yang pertama adalah setting waktu berlangsungnya cerita. Penulis menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi secara lambat dan terbelakang di Papua. Jauh dari tanah tempat berpusatnya hiruk pikuk negara (baca: Pulau Jawa) membuat Papua tampak begitu jauh dari peradaban. Apalagi ditambah dengan setting tempat yang merupakan pedalaman Papua dan masyarakatnya yang masih percaya dengan leluhur dan menganut dinamisme. Akhirnya penulis mampu menjawab di akhir cerita.